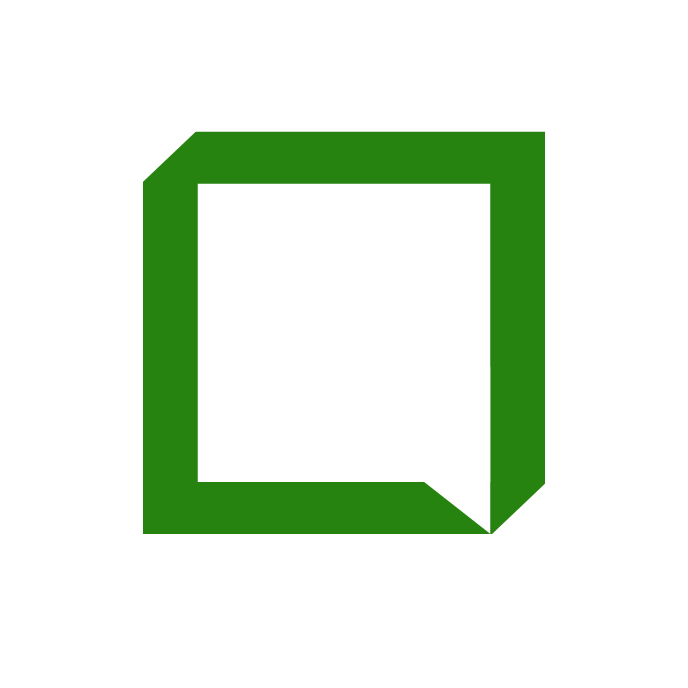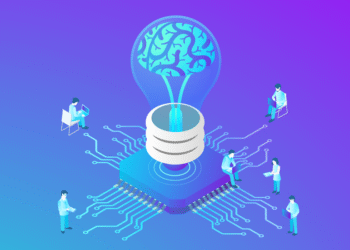Oleh: Muhammad Haykal, B.A., M.A*
Di panggung internasional, Indonesia sedang menari dengan anggun. Bersama Brasil, kita tengah merajut sebuah aliansi strategis yang digadang-gadang akan mengubah peta politik iklim global. Narasi yang dibangun sangat memukau: dua negara pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia bersatu untuk menjadi Climate Superpower. Istilah “OPEC-nya Hutan Hujan” mulai didengungkan, menjanjikan posisi tawar yang kuat dalam pasar karbon dan negosiasi lingkungan global. Sebagaimana diulas dalam analisis Katadata baru-baru ini, kolaborasi ini adalah peluang emas untuk menjaga “paru-paru dunia” sekaligus mendatangkan keuntungan ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon yang adil.
Namun, ketika kita mengalihkan pandangan dari ruang sidang ber-AC di Rio de Janeiro atau Jakarta ke wilayah barat Indonesia, pemandangan yang tersaji sangat kontras dan menyayat hati. “Paru-paru dunia” yang kita banggakan itu sedang batuk darah. Sejak akhir November 2025, Sumatera-khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat-dilanda bencana hidrometeorologi dahsyat. Banjir bandang menyapu permukiman, tanah longsor memutus nadi logistik, dan infrastruktur vital lumpuh total.
Artikel ini bertujuan untuk membedah paradoks tersebut secara mendalam. Bagaimana kita bisa mendamaikan ambisi global Indonesia sebagai penjaga iklim dengan kegagalan domestik dalam mitigasi bencana ekologis? Apakah kolaborasi dengan Brasil hanya akan menjadi etalase diplomatik, atau bisakah ia menjadi momentum untuk menata ulang tata kelola hutan kita yang sedang sekarat?
Aliansi Dua Raksasa-Mimpi Besar di Panggung Global
Tidak dapat dipungkiri, langkah Indonesia merangkul Brasil adalah manuver geopolitik yang cerdas. Secara statistik, kedua negara ini memegang kunci stabilitas iklim planet bumi. Hutan Amazon di Brasil dan hutan hujan tropis di Kalimantan, Papua, serta Sumatera di Indonesia adalah penyerap karbon (carbon sink) alamiah terbesar yang tersisa.
Dalam konteks analisis Katadata, peluang kolaborasi ini mencakup tiga aspek strategis:
- Dominasi Pasar Karbon: Selama ini, harga kredit karbon seringkali didikte oleh negara-negara maju (Global North) dengan harga yang sangat murah, seolah-olah fungsi hutan hanyalah komoditas pelengkap. Dengan bersatu, Indonesia dan Brasil memiliki leverage untuk menetapkan standar harga dasar karbon yang lebih tinggi dan adil. Ini adalah logika kartel yang positif; jika Anda menguasai suplai (dalam hal ini, jasa lingkungan penyerapan karbon), Anda berhak menentukan harga.
- Posisi Tawar Melawan Tekanan Dagang: Kedua negara menghadapi tantangan serupa terkait regulasi lingkungan yang diterapkan oleh Uni Eropa, seperti EUDR (European Union Deforestation Regulation). Regulasi ini sering dianggap sebagai hambatan non-tarif bagi komoditas unggulan seperti sawit, kopi, dan kedelai. Dengan satu suara, Indonesia dan Brasil bisa menuntut transparansi dan keadilan, memastikan bahwa standar keberlanjutan tidak menjadi alat proteksionisme terselubung.
- Pertukaran Teknologi dan Konservasi: Brasil memiliki pengalaman panjang (dengan segala pasang surutnya) dalam pemantauan hutan berbasis satelit melalui INPE (National Institute for Space Research). Indonesia, di sisi lain, memiliki keunggulan dalam tata kelola lahan gambut. Kolaborasi teknis ini menjanjikan lonjakan kapasitas dalam memantau kesehatan hutan secara real-time.
Di atas kertas, aliansi ini sempurna. Indonesia memposisikan dirinya bukan lagi sebagai objek bantuan iklim, melainkan sebagai subjek penentu kebijakan iklim. Namun, legitimasi moral dan operasional dari status “Climate Superpower” ini diuji bukan di meja perundingan PBB, melainkan di lapangan, di mana rakyat berhadapan langsung dengan konsekuensi pengelolaan alam.
Realitas Kelam di Halaman Belakang-Sumatera Tenggelam
Saat para diplomat berbicara tentang masa depan, warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar sedang bertarung nyawa demi hari ini. Bencana banjir yang terjadi di penghujung tahun 2025 ini bukanlah anomali cuaca biasa. Intensitas hujan memang tinggi-sebuah dampak nyata dari perubahan iklim global-namun dampak destruktifnya diperparah oleh degradasi daya dukung lingkungan yang akut.
Mari kita lihat faktanya. Aceh, yang memiliki Ekosistem Leuser sebagai salah satu benteng terakhir biodiversitas dunia, mengalami kelumpuhan infrastruktur yang masif. Laporan terbaru menyebutkan bahwa pasokan listrik terganggu hingga tujuh hari karena gardu induk dan jalur distribusi hancur diterjang banjir. Logistik seberat puluhan ton harus dikirim menggunakan helikopter karena jalan darat putus total. Ini adalah gambaran sebuah wilayah yang kehilangan daya lenting (resilience) ekologisnya.
Banjir ini adalah pesan alam bahwa “paru-paru” tersebut sedang sakit. Hutan di pegunungan Bukit Barisan, yang seharusnya berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air hujan, telah kehilangan kemampuannya. Alih fungsi lahan untuk pertambangan ilegal, perambahan hutan untuk perkebunan monokultur, dan pembangunan infrastruktur yang menabrak zona merah konservasi telah menciptakan “jalan tol” bagi air bah untuk meluncur bebas ke permukiman penduduk.
Ironi ini semakin tajam jika kita menyandingkan narasi diplomasi dengan data bencana. Kita “menjual” jasa hutan kita ke dunia internasional sebagai penyerap emisi global, tetapi di tingkat lokal, hutan tersebut gagal memberikan jasa lingkungan paling dasar: melindungi rakyat dari bencana hidrometeorologi.
Ekonomi Hijau vs Ekonomi Bencana
Salah satu poin krusial dalam diskusi Indonesia-Brasil adalah tentang Green Economy. Namun, bencana Sumatera memberikan pelajaran brutal tentang Disaster Economics.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa pada Oktober 2025, neraca perdagangan Aceh mengalami defisit USD 11,57 juta. Ekspor turun, impor melonjak. Mengapa? Salah satu faktor utamanya adalah terganggunya rantai pasok akibat kerusakan infrastruktur. Ketika jalan putus dan jembatan roboh, komoditas CPO dan kopi tidak bisa mencapai pelabuhan. Biaya logistik meroket, dan inflasi pangan mengancam.
Di sinilah letak kegagalan kalkulasi kita selama ini. Seringkali, pemerintah daerah dan pusat tergiur oleh pendapatan jangka pendek dari eksploitasi hutan (PAD dari tambang, pajak sawit, dll). Namun, mereka lupa memasukkan “Biaya Bencana” ke dalam neraca ekonomi tersebut.
Berapa triliun rupiah yang harus dikucurkan negara untuk memperbaiki jalan Trans-Sumatera yang longsor? Berapa kerugian PLN akibat gardu yang rusak? Berapa kerugian produktivitas masyarakat yang listriknya mati selama sepekan? Berapa biaya kesehatan akibat wabah penyakit pasca-banjir?
Jika dikalkulasi secara jujur, biaya pemulihan bencana ini kemungkinan besar jauh melampaui pendapatan yang didapat dari aktivitas ekstraktif yang merusak hutan tersebut.
Kolaborasi Indonesia-Brasil seharusnya membuka mata para pembuat kebijakan tentang valuasi ekonomi hutan yang sesungguhnya. Hutan bukan hanya aset karbon yang bisa dijual kreditnya. Hutan adalah infrastruktur mitigasi bencana termurah dan paling efektif. Menjaga Leuser tetap utuh, misalnya, secara ekonomi lebih menguntungkan dalam jangka panjang karena mencegah kerugian triliunan rupiah akibat banjir, dibandingkan mengonversinya menjadi lahan tambang yang keuntungannya hanya dinikmati segelintir elit namun risikonya ditanggung seluruh rakyat.
Lessons dari Brasil, Mengaca pada Diri Sendiri
Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari Brasil dalam konteks bencana ini? Brasil, di bawah kepemimpinan Presiden Lula da Silva, telah melakukan comeback yang kuat dalam kebijakan lingkungan setelah masa kelam di era Jair Bolsonaro di mana deforestasi Amazon mencapai rekor tertinggi.
Pelajaran pertama adalah Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Brasil mengaktifkan kembali polisi lingkungan federal dan militer untuk menindak pembalakan liar dan penambangan emas ilegal di Amazon. Mereka menggunakan citra satelit untuk mendeteksi pembukaan lahan baru dalam hitungan jam dan mengirim tim intervensi segera.
Di Sumatera, kita sering melihat pola pembiaran. Tambang ilegal (PETI) beroperasi terang-terangan di hulu sungai. Perambahan hutan lindung untuk kebun sayur atau sawit seringkali didiamkan atas nama “ekonomi rakyat” atau dibekingi oleh oknum aparat. Jika Indonesia ingin serius bermitra dengan Brasil, kita harus mengadopsi ketegasan penegakan hukum ini. Tanpa law enforcement yang kuat, komitmen iklim hanyalah macan kertas.
Pelajaran kedua adalah Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Hutan Amazon yang paling terjaga adalah wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat. Di Indonesia, pengakuan Hutan Adat masih berjalan lambat. Padahal, kearifan lokal masyarakat di sekitar Leuser atau Danau Toba seringkali lebih efektif menjaga keseimbangan alam daripada regulasi negara yang kaku namun koruptif.
Sebaliknya, Brasil juga bisa belajar dari Indonesia mengenai manajemen gambut dan restorasi mangrove. Kerjasama ini haruslah menjadi transfer of knowledge yang jujur, di mana kedua negara mengakui kelemahan domestiknya masing-masing dan berkomitmen untuk memperbaikinya, bukan sekadar aliansi dagang untuk melawan Uni Eropa.
Urgensi Penetapan Status Bencana dan Koreksi Kebijakan
Kembali ke konteks banjir Sumatera. Perdebatan mengenai status “Bencana Nasional” vs “Bencana Daerah” yang kini mengemuka menunjukkan betapa birokratisnya cara pandang kita terhadap krisis. BNPB berargumen bahwa pemerintahan daerah belum lumpuh total, sehingga status nasional tidak diperlukan.
Argumen ini berbahaya. Dalam perspektif perubahan iklim—isu yang menjadi inti kerjasama Indonesia-Brasil—bencana hari ini tidak bisa lagi diukur dengan parameter konvensional 20 tahun lalu. Eskalasi dampaknya eksponensial. Ketika tiga provinsi lumpuh sekaligus, ketika listrik padam massal, dan ketika dokter anak (IDAI) berteriak bahwa layanan kesehatan kolaps, itu adalah tanda bahwa kapasitas daerah sudah terlampaui.
Menolak menaikkan status bencana dengan alasan administratif, sementara di saat yang sama kita berpidato di forum global tentang kepemimpinan iklim, adalah sebuah disonansi kognitif. Negara harus hadir secara total. Dana Siap Pakai (DSP) harus dikucurkan tanpa hambatan birokrasi.
Lebih jauh lagi, momentum bencana ini harus menjadi titik balik (turning point) bagi kebijakan tata ruang di Sumatera. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dan Sumut harus diaudit total. Izin-izin konsesi yang berada di zona rawan bencana atau hulu daerah aliran sungai (DAS) harus dicabut atau dievaluasi ulang.
Program “Rehabilitasi Hutan dan Lahan” tidak boleh lagi sekadar proyek menanam bibit yang kemudian mati ditinggal pergi. Ia harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan masyarakat lokal dengan insentif ekonomi yang nyata—mungkin didanai dari skema perdagangan karbon yang sedang dirancang bersama Brasil.
Menuju “Climate Superpower” yang Otentik
Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin dunia dalam isu iklim. Aliansi dengan Brasil adalah langkah awal yang brilian. Namun, predikat Climate Superpower bukanlah sebuah hadiah; ia adalah sebuah beban tanggung jawab.
Tanggung jawab itu bukan kepada PBB, bukan kepada pembeli kredit karbon di Eropa, melainkan kepada rakyat Indonesia sendiri. Kepada anak-anak di Aceh Utara yang sekolahnya terendam lumpur, kepada petani di Tanah Datar yang sawahnya hilang disapu lahar dingin, dan kepada warga Medan yang rumahnya menjadi langganan banjir tahunan.
Jika kita gagal melindungi mereka, maka diplomasi “paru-paru dunia” ini tak lebih dari sebuah greenwashing raksasa tingkat negara. Kita seolah-olah menjadi pahlawan bagi penduduk bumi di belahan lain dengan menyerap karbon mereka, sementara membiarkan penduduk kita sendiri tenggelam karena kerusakan ekosistem yang sama.
Kolaborasi Indonesia-Brasil harus dimaknai ulang. Bukan sekadar tentang berapa Dollar yang bisa kita dapat dari hutan kita, tapi tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan politik dan ekonomi dari aliansi tersebut untuk membiayai pemulihan ekologis di dalam negeri.
Kita butuh dana, teknologi, dan kemauan politik untuk melakukan reforestasi masif, membersihkan sungai, menindak mafia tanah, dan membangun infrastruktur yang tahan iklim. Jika hasil dari kerjasama dengan Brasil bisa diarahkan ke sana, maka barulah kita pantas disebut sebagai raksasa iklim.
Jangan Sampai Paru-Paru Itu Bocor Permanen
Banjir di Sumatera adalah alarm nyaring yang membangunkan kita dari mimpi indah diplomasi tingkat tinggi. Ia mengingatkan kita bahwa alam tidak bisa diajak bernegosiasi dengan MoU atau pidato kenegaraan. Alam bekerja dengan hukum fisika dan biologi: jika kau rusak daya dukungnya, ia akan mencari keseimbangan baru, seringkali melalui cara yang destruktif bagi manusia.
Mari kita dukung penuh kolaborasi Indonesia-Brasil ini, namun dengan catatan kaki yang tebal: Perbaiki dulu rumah sendiri. Jadikan perlindungan terhadap Leuser dan Bukit Barisan sebagai prioritas keamanan nasional, setara dengan prioritas pertahanan militer. Karena pada akhirnya, ancaman terbesar bagi kedaulatan kita hari ini bukanlah invasi militer asing, melainkan krisis ekologis yang mampu melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hitungan hari.
Tanpa hutan yang sehat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, Indonesia tidak akan menjadi Climate Superpower. Kita hanya akan menjadi negara kepulauan yang rapuh, yang terus-menerus sibuk mengurusi tanggap darurat, menghitung kerugian, dan mengubur korban jiwa, sementara dunia luar bertepuk tangan atas pidato kita yang indah tentang masa depan bumi yang hijau.
Sudah saatnya diplomasi iklim kita menjejak bumi. Dari Rio de Janeiro, kembali ke tepian Krueng Aceh dan Sungai Deli. Di sanalah pertaruhan yang sesungguhnya berada.
*Penulis : Alumni Marmara University, Istanbul dan Ketua Yayasan Tarara Global Humanity