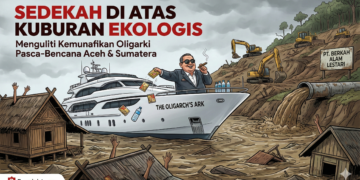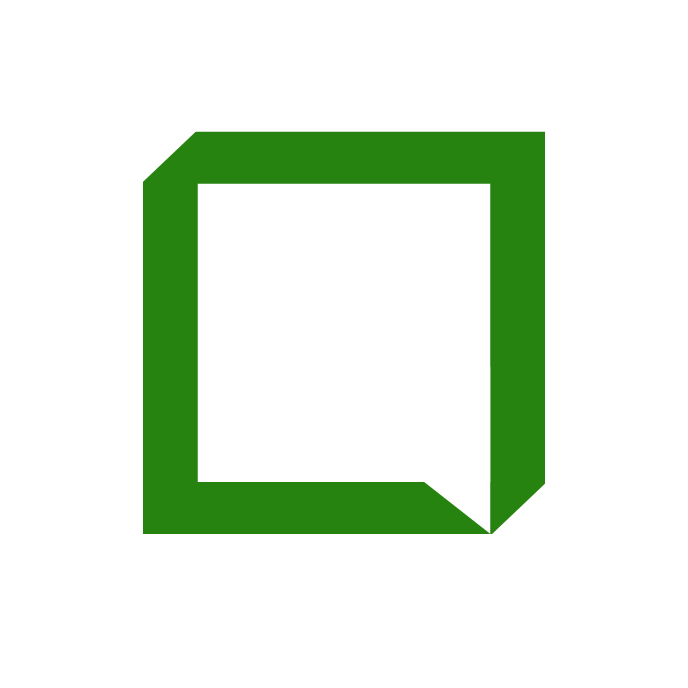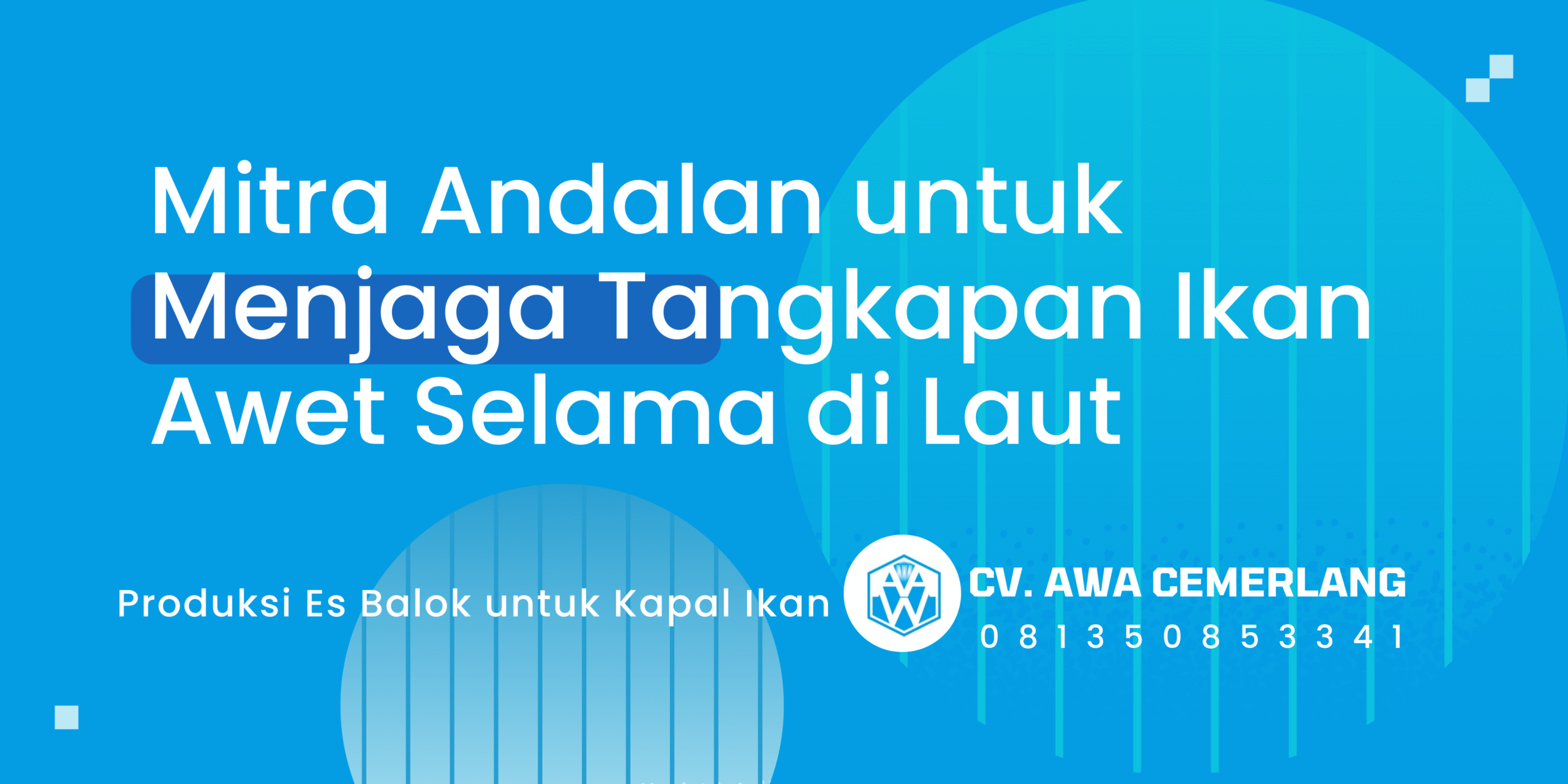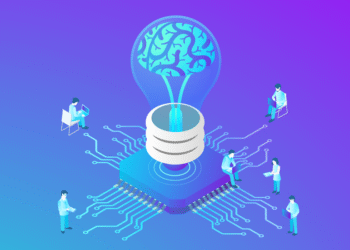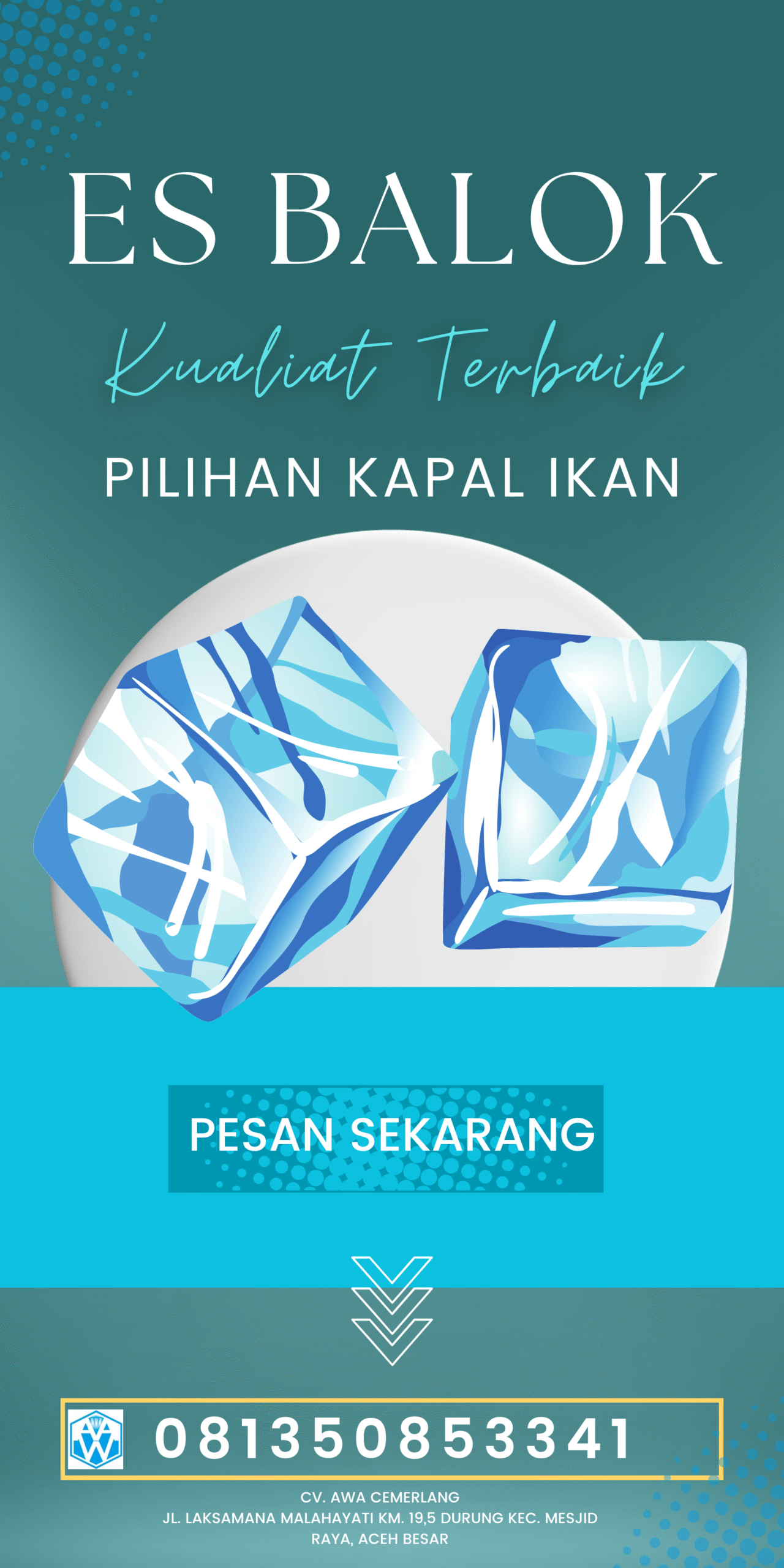Oleh: Tgk Muhammad Razi*
Sejak penandatanganan Perjanjian Helsinki tahun 2005, dua dekade yang lalu, Aceh memperoleh status istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus). Status ini tidak hanya menjadi jalan keluar dari konflik berkepanjangan, tetapi juga instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperkuat demokrasi lokal, serta menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Hampir dua dekade berlalu, publik kini mempertanyakan: sejauh mana Otonomi Khusus telah menjawab harapan itu, dan apa saja tantangan yang masih mengganjal implementasinya?
Janji Sejahtera dalam Bingkai Otonomi
Otonomi Khusus Aceh dirancang dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, baik dalam aspek politik, hukum, maupun ekonomi. Salah satu instrumen utamanya adalah alokasi Dana Otsus yang nilainya sangat signifikan. Sejak 2008 hingga 2025, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 200 Triliun (BPS Aceh; Kemenkeu RI, 2024). Angka ini menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah penerima dana transfer pusat terbesar di Indonesia.
Harapannya, dana tersebut dapat menjadi modal bagi transformasi ekonomi ( terutama berbasis syariah), perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengentasan kemiskinan. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan legitimasi hukum yang kuat (UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh), Aceh seharusnya mampu membangun model pembangunan daerah yang lebih mandiri dan kontekstual. Kenapa ini masih belum tercapai?
Realitas yang Mengganjal
Namun, implementasi Otonomi Khusus di Aceh tidak sepenuhnya berjalan mulus. Data BPS Aceh (2025) menunjukkan angka kemiskinan di Aceh masih sekitar 12,33%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 8,47% (BPS RI, 2025). Tingkat pengangguran terbuka pun masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera.
Di sisi lain, tata kelola dana Otsus kerap menjadi sorotan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti lemahnya perencanaan, tumpang tindih program, hingga rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Akibatnya, dana yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, justru sering terserap untuk belanja birokrasi dan program yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut penulis sendiri bahwa permasalahan utama Otonomi Khusus di Aceh terletak pada lemahnya tata kelola dan akuntabilitas. Dana yang sangat besar tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif, sehingga rawan disalahgunakan dan tidak menyentuh akar permasalahan rakyat.
Selain itu, Otonomi Khusus di Aceh sering kali terjebak dalam tarik-menarik politik lokal. Dinamika antara partai lokal, ulama, dan elite pemerintahan acap kali lebih dominan dibandingkan diskursus mengenai kebutuhan rakyat banyak. Dalam konteks ini, Otsus masih belum sepenuhnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, melainkan cenderung menjadi arena kontestasi kepentingan elite.
Menimbang Perbandingan dan Kisah Sukses
Belajar dari pengalaman devolusi di Skotlandia, Inggris, otonomi daerah dapat berjalan lebih efektif ketika mekanisme checks and balances diperkuat dan partisipasi publik dijamin dalam setiap proses pengambilan keputusan. Skotlandia berhasil mengarahkan devolusi untuk memperkuat kapasitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, meskipun tetap berada dalam kerangka United Kingdom. Bahkan, Skotlandia memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif dan lapisan (band) pajak penghasilan sendiri berkat pelimpahan sebagian kekuasaan perpajakan dari pemerintah pusat Inggris. Hal ini memungkinkan Skotlandia menyesuaikan sistem pajaknya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan wilayahnya.
Aceh seharusnya juga bisa bergerak ke arah itu. Meskipun tantangan besar masih menghadang, ada pula kisah sukses kecil yang bisa menjadi contoh. Di beberapa gampong (desa), pemanfaatan dana desa yang transparan dan berbasis musyawarah telah berhasil membangun infrastruktur dasar, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menggerakkan ekonomi lokal. Ini menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, dana otonomi bisa membawa dampak nyata bagi masyarakat.
Jalan Ke Depan
Menyadari tantangan tersebut, setidaknya ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh:
- Reformasi tata kelola keuangan daerah dengan sistem yang lebih transparan, berbasis digital, dan diawasi oleh lembaga independen maupun masyarakat sipil.
- Penguatan kapasitas kelembagaan agar birokrasi Aceh tidak hanya mengelola anggaran, tetapi juga mampu merancang program yang visioner dan berorientasi pada keberlanjutan.
- Mendorong partisipasi publik, termasuk ulama, akademisi, dan komunitas lokal, dalam proses perencanaan pembangunan.
- Diversifikasi ekonomi berbasis syariah, dengan mengoptimalkan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, energi terbarukan, dan UMKM.
Otonomi Khusus Aceh adalah anugerah politik sekaligus amanah sejarah. Ia lahir dari konflik dan darah, sehingga implementasinya harus sungguh-sungguh diarahkan pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Tantangan implementasi memang nyata, mulai dari tata kelola anggaran hingga dinamika politik lokal. Namun, peluang untuk menjadikannya sebagai model pembangunan berbasis kearifan lokal dan syariah tetap terbuka lebar.
Pertanyaannya kini: apakah elite politik dan birokrasi di Aceh berani melampaui kepentingan jangka pendek untuk benar-benar menjadikan Otonomi Khusus sebagai jalan sejahtera bagi seluruh rakyat Aceh?
*Penulis: Alumni S2 Perbandingan Hukum dari Ahmad Ibrahim Kulliyah of Law, IIUM Malaysia, dan juga dosen hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STIS Nahdhatul Ulama Aceh.