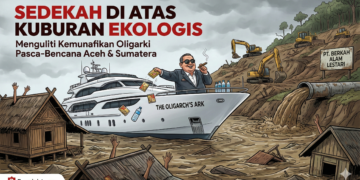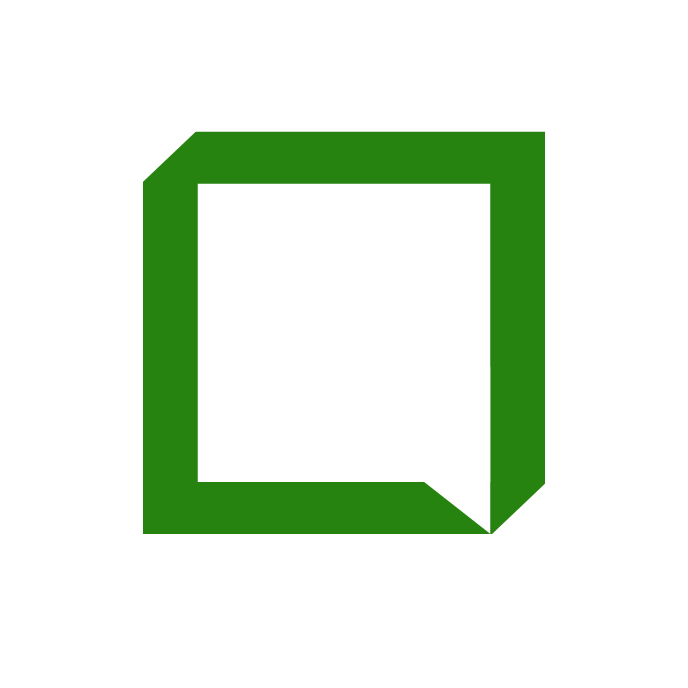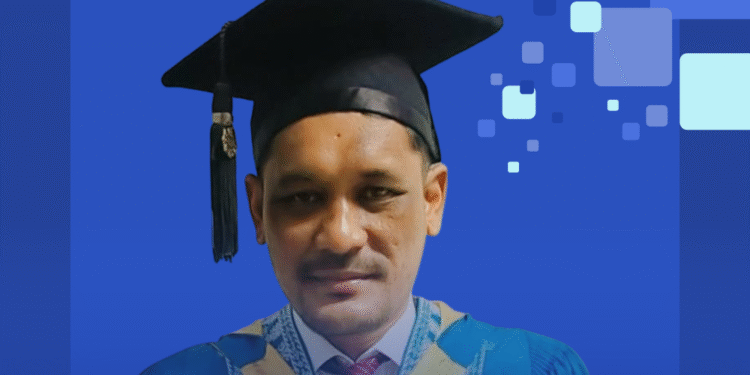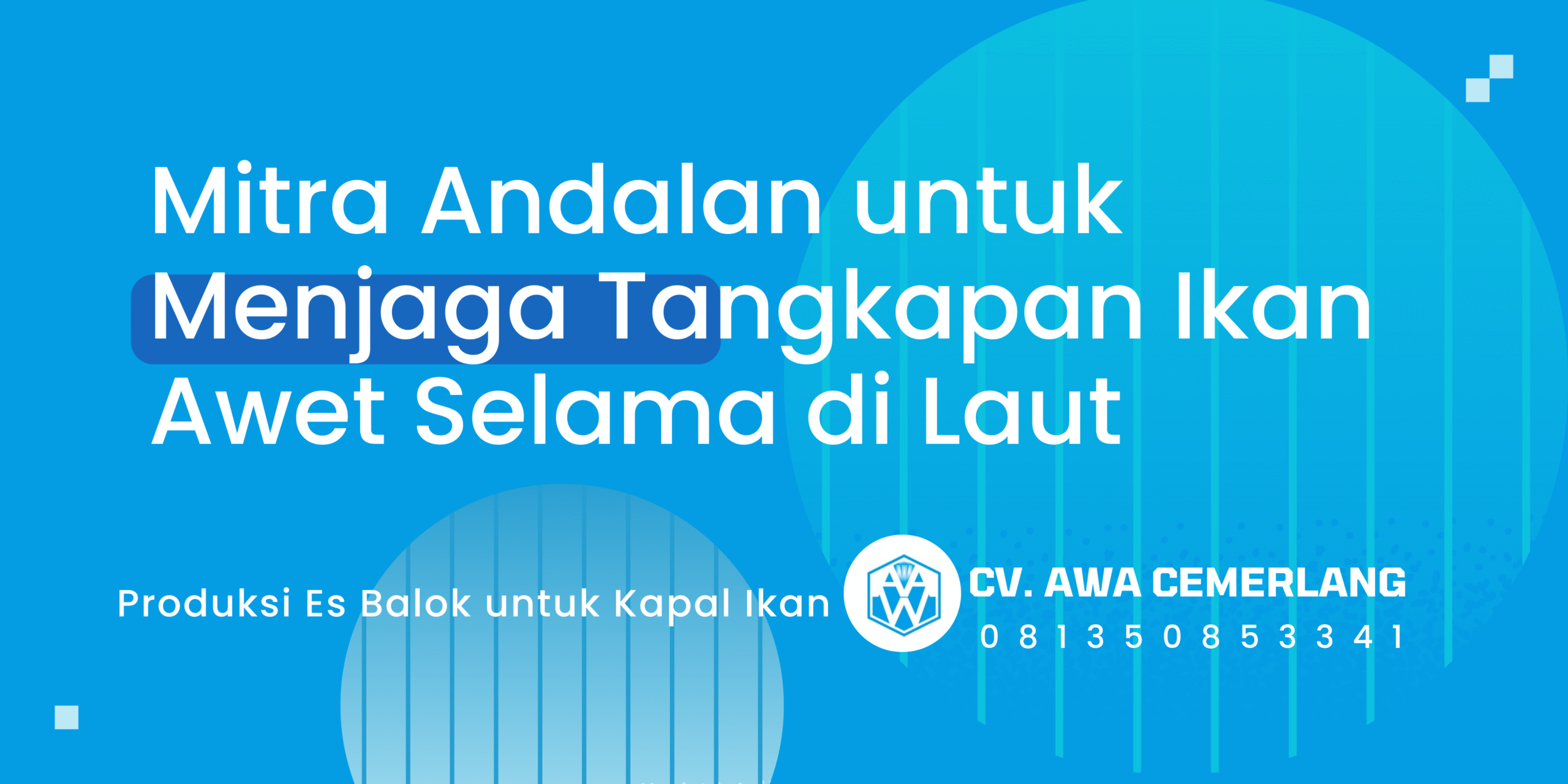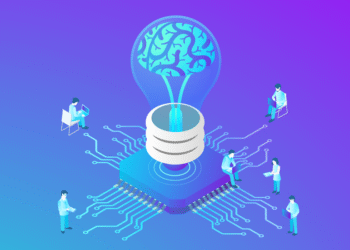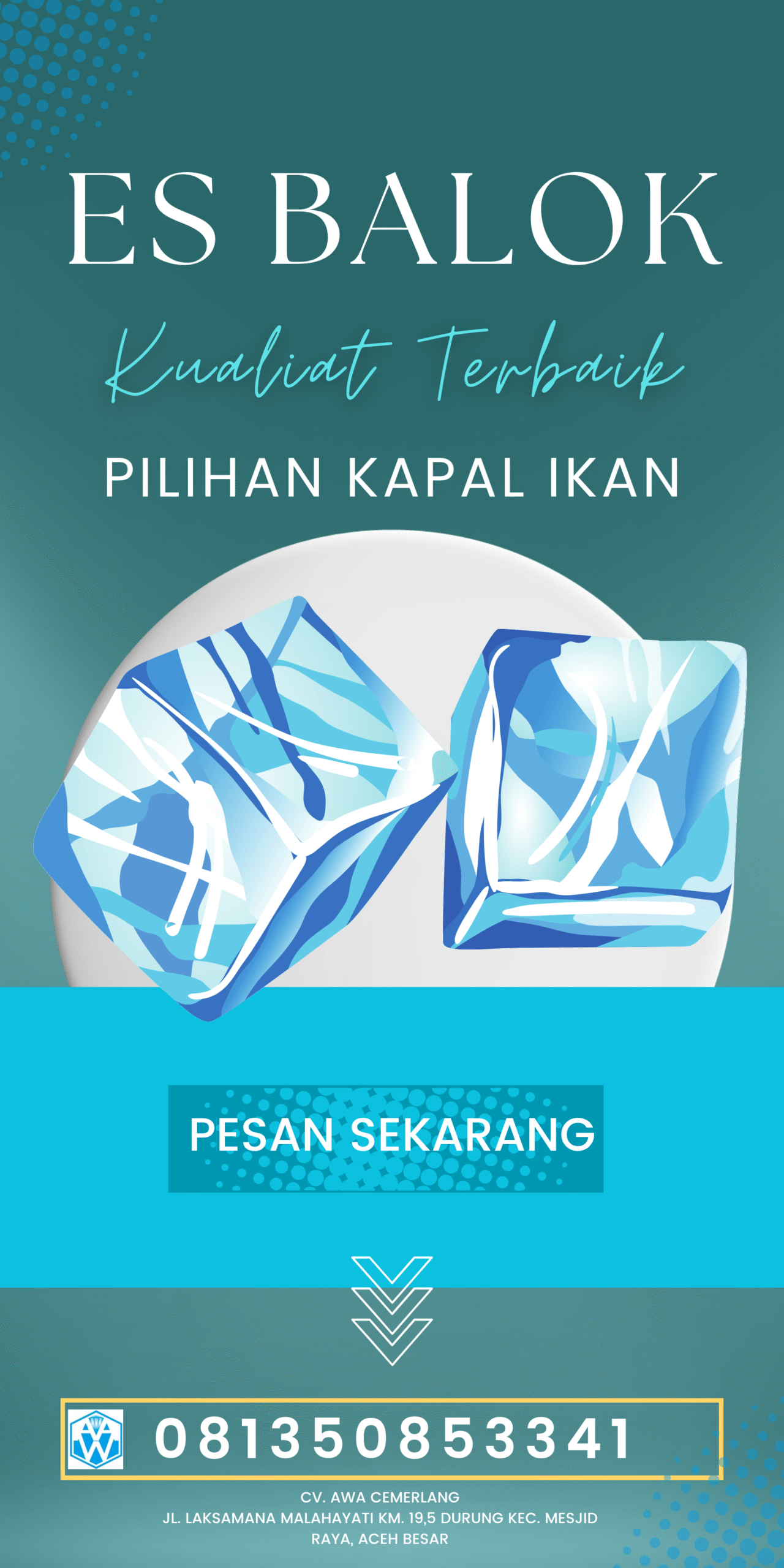Oleh: Muhammad Jais, S.E.,M.Sc.IBF*
Perkembangan bank syariah di Indonesia selalu menjadi diskursus menarik, baik di ruang akademik maupun praktis. Dialog kritis antara para pemikir Muslim memperlihatkan adanya perbedaan perspektif mendasar: apakah bank syariah yang ada saat ini merupakan solusi riil bagi umat atau sekadar “variasi” dari sistem perbankan ribawi yang dikemas dengan istilah syariah. Salah satu pandangan menegaskan bahwa dalam prinsip syariah, akad yang telah disepakati tidak boleh diubah karena akad merupakan kontrak yang mengikat hingga akhir. Oleh karena itu, perubahan nilai akibat dinamika ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk merombak kesepakatan awal. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar syariah yang menolak segala bentuk riba, karena riba termasuk dalam kategori dosa besar (kabāʾir) yang tidak bisa ditoleransi meskipun dengan alasan kebutuhan ekonomi.
Bank Syariah sebagai Ijtihad Institusional
Di sisi lain, muncul argumen bahwa keberadaan bank—termasuk bank syariah—merupakan kebutuhan mendesak masyarakat modern. Dalam konteks tersebut, umat Islam masih berhadapan dengan sistem ribawi global yang sulit dihindari. Oleh karena itu, bank syariah dipandang sebagai bentuk ijtihad institusional yang dimaksudkan untuk meminimalisasi keterjeratan umat pada praktik riba, meskipun dalam praktiknya masih belum sepenuhnya bebas dari logika kapitalisme. Lebih lanjut, persoalan utama lain terletak pada kerangka hukum dan sistem keuangan nasional maupun global. Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia Tahun 1992, misalnya, mendefinisikan bank semata sebagai lembaga intermediasi, bukan pelaku bisnis riil. Konsekuensinya, bank syariah tetap terjebak dalam pola pikir dan mekanisme kapitalistik, sehingga perbedaan antara bank syariah dan konvensional kerap hanya sebatas istilah akad. Inilah yang membuat sebagian pengamat menilai bahwa meskipun diniatkan sebagai “ijtihad maslahat”, hasil akhirnya masih menyisakan praktik ribawi dalam balutan akad syariah.
Tantangan Purifikasi
Diskursus mengenai arah dan masa depan bank syariah di Indonesia mengerucut pada pertanyaan fundamental: bagaimana mewujudkan bank syariah yang benar-benar bebas dari riba tanpa harus mengisolasinya dari sistem perbankan nasional maupun global? Sebagian pihak berpandangan bahwa jika bank syariah dipaksa untuk bersifat eksklusif dan terpisah total, umat justru akan lebih memilih bank konvensional karena lebih praktis dan terhubung dengan jaringan keuangan internasional. Namun, pihak lain menegaskan bahwa kompromi permanen dengan sistem ribawi hanya akan melahirkan bank “berlabel syariah” tanpa ruh syariah. Dalam literatur akademik, Guru Besar Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, Prof. Syahrizal Abbas membagi perjalanan bank Syariah di Indonesia ke dalam tiga fase, yaitu introduction, recognition, dan purification. Dua fase awal telah berhasil dilalui, dan kini tantangan terbesar terletak pada fase purifikasi yang bukan hanya membutuhkan perbaikan teknis, tetapi juga keberanian politik untuk menegakkan sistem ekonomi Islam secara kaffah. Perdebatan ini semakin menguat karena menyangkut dua hal mendasar: konstitusi nasional sebagai kerangka hukum positif yang berlaku, dan syariat Islam sebagai norma ilahiah yang menjadi ruh eksistensi bank syariah. Dari titik inilah muncul dua arus besar pemikiran, yaitu pandangan optimis dan pandangan kritis.
Pandangan optimis meyakini bahwa pengembangan bank syariah tetap dapat berjalan sesuai “aturan main” konstitusi nasional, meskipun perjalanan menuju bentuk idealnya akan berlangsung panjang. Keyakinan ini diperkuat oleh contoh Provinsi Aceh yang telah menerapkan single banking system melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, sebagai bukti bahwa purifikasi dapat diwujudkan secara bertahap melalui perjuangan kolektif dan kolaboratif. Sebaliknya, pandangan kritis menilai bahwa perubahan regulasi selama ini bersifat teknis-administratif dan tidak menyentuh substansi, sehingga purifikasi sejati mustahil dicapai selama perbankan syariah masih tunduk pada kerangka hukum sekuler yang berakar pada logika kapitalistik.
Menurut perspektif di atas, solusi hakiki hanya dapat diwujudkan dengan mengganti aturan main buatan manusia dengan hukum Allah SWT agar sistem perbankan benar-benar terbebas dari praktik riba. Kedua pandangan tersebut tidak harus diposisikan sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai refleksi dari dialektika panjang umat Islam dalam menegakkan syariah di tengah konteks negara modern. Oleh karena itu, jalan tengah yang dapat ditempuh adalah kerja kolektif dan kolaboratif: akademisi menyempurnakan konsep, ulama menegaskan batas syariah, regulator merancang instrumen yang aplikatif, dan negara menghadirkan keberanian politik untuk melakukan transformasi struktural. Dengan langkah demikian, bank syariah di Indonesia tidak sekadar menjadi variasi dari bank konvensional, melainkan benar-benar hadir sebagai solusi hakiki bagi umat Islam untuk terbebas dari jerat riba.
*Penulis: Alumni S2 Islamic Banking and Finance di International Islamic University Malaysia dan juga Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)