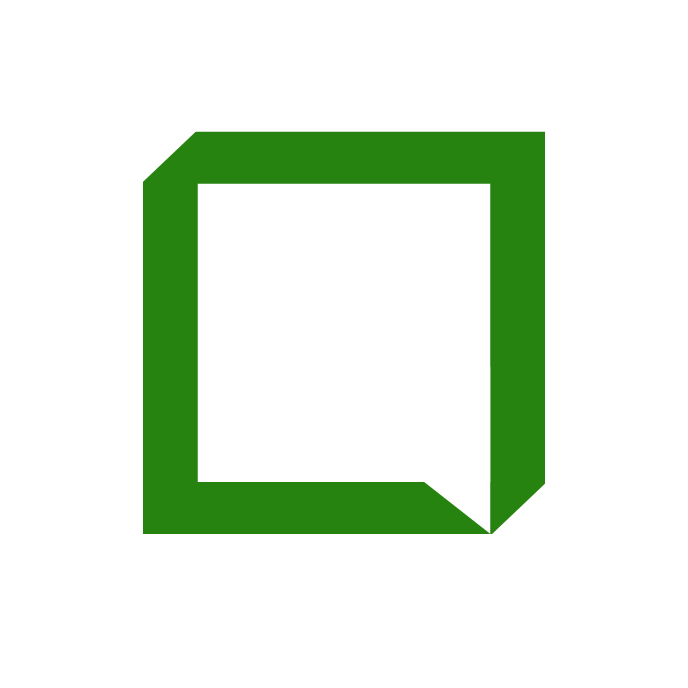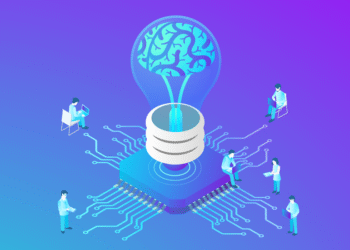Oleh: Tim Redaksi
Artikel di Katadata baru-baru ini menyuarakan urgensi menagih tanggung jawab kelompok kaya atas bencana ekologis. Premisnya benar, namun bagi kami di Aceh dan Sumatera yang baru saja kehilangan 430 nyawa (dan terus bertambah) akibat banjir bandang, narasi tersebut masih terlalu sopan.
Kita tidak sedang berbicara tentang orang kaya yang “lupa mematikan lampu” atau “terlalu sering naik pesawat pribadi”. Kita sedang berbicara tentang kejahatan struktural. Bencana yang menenggelamkan Aceh Tamiang, Aceh Selatan, hingga Sumatera Barat hari ini bukanlah “azab Tuhan” atau sekadar dampak perubahan iklim global yang abstrak. Ini adalah hasil dari akumulasi keserakahan segelintir elite—kelompok 1%—yang telah memprivatisasi keuntungan dari alam Sumatera dan mensosialisasi kerugiannya kepada rakyat jelata dalam bentuk air bah.
Mitos “Tanggung Jawab Bersama”
Selama bertahun-tahun, kita dicekoki narasi bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan “rayuan” ini juga baru-baru ini disampaikan oleh orang nomor satu di negeri ini ketika mengunjungi korban banjir di Aceh Tamiang. Rakyat kecil disuruh mengurangi kantong plastik dan hemat air. Padahal, data Oxfam dan World Inequality Lab konsisten menunjukkan: emisi dan kerusakan yang dihasilkan oleh gaya hidup dan (terutama) investasi kelompok super-kaya setara dengan gabungan emisi separuh penduduk bumi termiskin.
Di Aceh, ketimpangan ini terlihat telanjang. Petani kecil di hulu dituduh perambah hutan hanya karena membuka lahan setengah hektare untuk makan. Sementara itu, korporasi sawit dan tambang yang menguasai ribuan hektare di zona tangkapan air (catchment area)—yang izinnya dikeluarkan oleh pejabat yang “bermain mata” dengan oligarki—melenggang bebas.
Ketika banjir datang, rakyat kecil kehilangan rumah, sawah, dan nyawa. Apa yang hilang dari orang kaya pemilik konsesi itu? Mungkin hanya sedikit penurunan profit di laporan keuangan kuartal IV, yang dengan mudah ditutup oleh asuransi atau diversifikasi bisnis mereka di tempat lain.
Filantropi sebagai Pencucian Dosa
Poin paling kritis yang harus kita bedah adalah fenomena “CSR Bencana”. Pasca-bencana Desember 2025 ini, kita melihat perusahaan-perusahaan ekstraktif berlomba-lomba mengirimkan truk bantuan bertuliskan “Peduli Bencana”. Mereka menyumbang beras, mi instan, dan selimut.
Mari kita sebut ini apa adanya: Ini adalah penghinaan.
Mereka merusak ekosistem yang nilainya triliunan rupiah (fungsi penahan air, pencegah longsor, habitat satwa), lalu “menebusnya” dengan bantuan remah-remah senilai ratusan juta rupiah. Ini bukan tanggung jawab sosial; ini adalah biaya humas (PR cost) untuk mencuci dosa ekologis mereka. Mereka ingin terlihat sebagai pahlawan di tengah bencana yang mereka bantu ciptakan.
Menagih Lebih dari Sekadar Pajak
Artikel Katadata menyarankan mekanisme pajak kekayaan atau pajak karbon. Itu solusi teknokratis yang bagus, tapi tidak cukup. Untuk konteks Indonesia dan Aceh saat ini, kita butuh pendekatan yang lebih radikal:
- Audit Forensik dan Pemiskinan Perusak Lingkungan: Jangan hanya denda administratif. Gunakan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengejar aliran dana hasil kejahatan lingkungan. Jika perusahaan terbukti beroperasi di kawasan hutan lindung yang menyebabkan banjir bandang, aset pemiliknya harus disita untuk membiayai rekonstruksi wilayah terdampak.
- Stop “Greenwashing” Pejabat: Pejabat yang menerbitkan izin di zona merah bencana harus diseret ke pengadilan dengan pasal kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Absennya Bupati Aceh Selatan untuk umrah saat bencana adalah simbol betapa terputusnya elite politik kita dari penderitaan rakyat.
- Moratorium Total dan Penegakan Hukum: Bukan sekadar jeda perizinan, tapi pencabutan izin konsesi di seluruh hulu DAS kritis di Sumatera.
Menagih tanggung jawab orang kaya tidak bisa dilakukan dengan proposal santun atau imbauan moral. Bahasa yang mereka mengerti hanyalah profit dan aset.
Oleh karena itu, narasi harus diubah. Kita tidak meminta “sumbangan” atau “kepedulian” mereka. Kita menuntut ganti rugi penuh. Setiap nyawa yang melayang di Aceh dan Sumatera bulan ini memiliki harga yang harus dibayar, bukan oleh APBD yang defisit, melainkan oleh rekening-rekening gemuk yang membengkak dari hasil mengeruk perut bumi dan menggunduli hutan kita.
Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan hujan. Mulailah menunjuk hidung para “bandit lingkungan” yang bersembunyi di balik izin legal dan jubah filantropi.